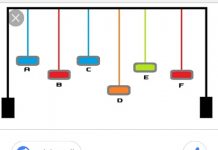Oleh: HELP-S
“Atuh Ibu Dokter, sih, kagak ikut BPJS. ‘Kan warganya pada nggak ikut BPJS juga. Repot kalau ada yang sakit,” tukas salah seorang kader posyandu.
Saya hanya tersenyum.
“Biar kata kagak nyuruh ikut BPJS, eta ge* Bu Dokter suka bantu warga yang sakit. Ga usah nyalahin Bu Dokter. Atah warah *,” bela seorang warga.
Warga di Parakan, tempat saya sering mengisi pengajian, sudah hapal tabiat saya. Kalau urusan dengan BPJS, pasti saya kabur duluan. Kalau ada kumpul-kumpul ngisi formulir BPJS, saya pasti tidak datang.
Bukan, bukan karena saya sok kaya merasa tidak butuh BPJS. Juga bukan semata-mata karena saya menganggap BPJS haram. Memang, saya berpendapat BPJS sama seperti asuransi dan saya khawatir akan kehalalannya. Namun bukan kapasitas saya untuk menjelaskan detail hukumnya dan memaksa orang lain mengikuti pendapat saya. Sikap saya menolak menjadi peserta BPJS lebih sebagai bentuk protes dengan kebijakan pemerintah yang menurut saya merupakan kemunduran hebat dalam hal pelayanan kesehatan.
Saya hanyalah seorang dokter kampung. Tidak memiliki jabatan apapun di puskesmas, apalagi di pemerintahan. Saya juga bukan kritikus kebijakan, apalagi dewan penasihat kabinet. Saya hanyalah seorang anak yang berpikir sederhana, dan tidak bisa berkutik ketika sebelum wafat Bapak berwasiat, “dadio dokter sing ngadem lan ngagem ati.*”
Secara literal, arti dari pesan tersebut adalah: jadilah dokter yang menyejukkan dan memegang hati. Maknanya, Bapak meminta saya menjadi dokter yang menentramkan hati pasien dan melayani sepenuh hati. Bukan dokter yang asal mengobati tanpa memperhitungkan kondisi masing-masing pasien. Juga bukan dokter yang bekerja semata-mata demi balik modal sebab sekolahnya dulu berbiaya mahal.
Izinkan saya menceritakan pengalaman menggantikan seorang rekan sejawat mengisi jaga di klinik BPJS sebuah perusahaan. Dalam satu shift (8 jam) saya harus melayani 50-100 pasien. Itu berarti untuk satu pasien saya cuma punya alokasi waktu konsultasi 4.8-9.6 menit, sudah termasuk menulis resep.
Saya jadi sedih. Bagaimana mungkin saya bisa melayani dengan hati kalau waktunya semepet itu. Jangankan pake hati, pake tangan saja sudah mak sliwer*. Bahkan stetoskop pun tidak menempel di badan pasien. Agar tetap bisa mengobrol dengan pasien, mungkin saya harus berbicara dengan kecepatan cahaya. Opsi lainnya, saya harus meminjam alat penghenti waktu seperti di film-film itu.
Saya ini termasuk yang suka ngoceh dan rada bawel terhadap pasien. Hobi saya menanyakan kehidupan sosial pasien dan menggali faktor resiko penyakitnya. Kepo, sih, memang, tapi ini penting karena tugas saya bukan hanya menulis resep dan melakukan pengobatan kuratif, melainkan juga edukasi personal sebagai langkah pengobatan sekunder.
Menurut saya, BPJS memberikan pelayanan setengah-setengah. Meskipun sudah membayar premi, pengguna kartu BPJS masih juga membayar obat-obatan lain. Plafon BPJS untuk satu penyakit sangat rendah, kalau tidak boleh dikatakan di bawah standar. Tidak heran, banyak pasien menggerutu, “sudahlah antrinya lama, sembuhnya juga lama.”
Ada seribu pertanyaan berkecamuk di kepala saya. Mengapa BPJS menetapkan plafon serendah ini? Bukankah iuran yang dikumpulkan BPJS sangat banyak sementara yang sakit hanya sebagian saja? Lantas kemanakah uang BPJS? BPK sudah mengaudit BPJS Kesehatan dan terus menerus menemukan masalah di lembaga ini. Apa benar seperti isu-isu yang selama ini diberitakan, bahwa BPJS rugi milyaran rupiah di pasar modal?
Saya hanya ingin mengingatkan tenaga kesehatan bahwa sistem jaminan kesehatan seperti ini merendahkan martabat kita sebagai penyedia layanan kesehatan. Bukan kita yang menetapkan plafon, bukan kita yang menolak pasien, namun kita yang dianggap tidak punya hati.
Mungkin kondisi kita di era BPJS ini meniru trend perfilman Disney, dimana hero jadi villain dan villain jadi hero. Kita tidak lagi menjadi hero bagi masyarakat. Justru kaum kapitalis yang jadi hero, padahal sesungguhnya merekalah villain sejati. Ibarat kata, kita ini villain by design. Terpaksa jadi penjahat.
Kelak, ketika bertemu dengan Bapak, saya tidak tahu harus menjawab apa saat beliau bertanya, “jadi dokter macam apa kamu?”
*
Eta ge : itu juga
Atah warah: tidak tahu sopan santun