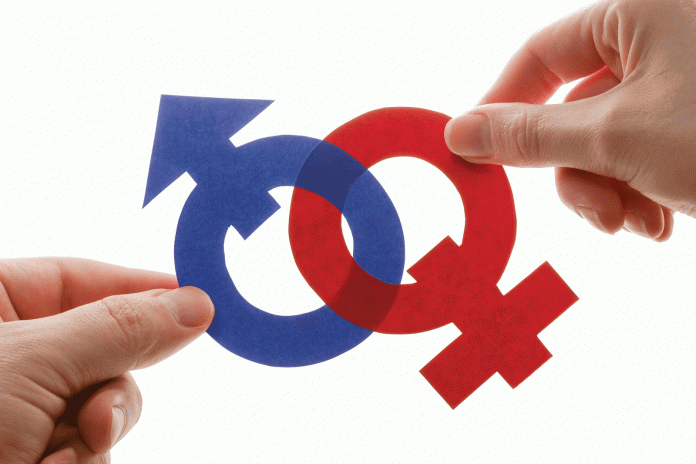Oleh: dr. Faizatul Rosyidah
Berdasarkan hasil survei Komnas Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 12 provinsi pada 2007 terungkap sebanyak 93,7% anak SMP dan SMU yang disurvei mengaku pernah melakukan ciuman, petting, dan oral seks. Dan, sebanyak 62,7% anak SMP yang diteliti mengaku sudah tidak perawan. Serta 21,2% remaja SMA yang disurvei mengaku pernah melakukan aborsi. Dan lagi, 97% pelajar SMP dan SMA yang disurvei mengaku suka menonton film porno (Media Indonesia,19/7/08)
Data tersebut tak pelak, menambah miris dan keprihatinan kita akan perilaku seksual remaja kita yang semakin hari semakin liberal saja. Berbagai analisa pun dilakukan. Salah satu pendapat yang kemudian cukup mengemuka adalah bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh remaja tentang kesehatan reproduksi mereka sehingga mereka melakukan perilaku seksual yang beresiko pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dengan berbagai konsekuensinya ataupun beresiko pada tertularnya penyakit-penyakit menular seksual. Dari asumsi ini, maka digencarkanlah upaya pemberian informasi seputar kesehatan reproduksi kepada remaja dengan bungkus ’Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja’ atau yang biasa disingkat KRR.
Target dari Pendidikan KRR ini adalah untuk mewujudkan perilaku seksual remaja yang aman dan sehat. Perilaku seksual remaja yang aman artinya perilaku seksual remaja yang tidak mengantarkan mereka pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan berikut resiko yang menyertainya. Sehat, artinya perilaku seksual remaja tersebut tidak mengantarkan remaja tertular penyakit menular seksual. Strategi yang dilakukan adalah mengkampanyekan perilaku seksual remaja yang aman dan sehat tersebut melalui seminar, pelatihan, talk show, buzz group, konsultasi, hingga bagi-bagi kondom. Subyek yang dilibatkan pun beragam; dari kalangan birokrat hingga para remaja yang diharapkan bisa menjadi agen penyampai pesan yang lebih mudah diterima oleh teman sebayanya. Media yang digunakan pun sangat variatif; dari brosur, leaflet, buklet, hingga game dan kuis yang memang sangat menarik bagi para remaja kita. Meski demikian variatif pelaku dan media yang digunakan, namun isi pesan yang disampaikan tetaplah sama, yaitu kampanye ABCD (Abstinensia, Be faithful, use Condom, no Drug) yang diiringi dengan implementasi kebijakan kondomisasi dan harm reduction. Sebuah kebijakan yang memang diimplementasikan di seluruh dunia, dengan digawangi UNAIDS dan WHO, termasuk di Indonesia.
Sekilas, slogan dan kampanye yang dibawa oleh pendidikan KRR ini sangat melegakan dan ’seolah’ bisa diharapkan memperbaiki perilaku seksual remaja kita yang liberal dan penuh resiko tersebut menjadi perilaku seksual yang tidak lagi liberal dan beresiko. Itulah perilaku seksual remaja yang aman, sehat dan bertanggung jawab. Benarkah demikian?
’Penyesatan’ di balik Slogan ’Pendidikan’
Dikatakan sebuah tindakan adalah pendidikan, jika di dalamnya dilakukan sebuah proses untuk membuat anak didik menjadi orang yang secara kognitif menjadi tahu dari ketidaktahuannya akan sesuatu kebenaran, secara afektif kemudian menerima kebenaran tersebut dengan penuh kerelaan, dan secara psikomotor kemudian bisa kita lihat bagaimana kebenaran yang sudah dipahaminya tersebut dia implementasikan dalam perilakunya sehari-hari. Nah pertanyaan yang mestinya muncul dan harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita mengadopsi dan melakukan pendidikan KRR ini adalah: ”Benarkah Kampanye ABCD adalah sebuah Pendidikan bagi remaja kita?” Mari kita lihat!
Sebelum kampanye ABCD dilakukan, dalam setiap penyampaian Pendidikan KRR selalu diawali dengan mengajak remaja untuk memahami proses pubertas yang mereka alami, dengan berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh (fisik), mental dan libido mereka. Benang merahnya adalah bahwa eksplorasi seksual pada masa pubertas ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh remaja, karena kondisi libido mereka yang memang lagi tinggi-tingginya. Namun agar tidak sampai terjatuh pada resiko mengalami kehamilan tidak diinginkan dan tertular penyakit menular seksual, yang seringkali menjatuhkan remaja kita pada resiko lain berikutnya (putus sekolah, aborsi hingga meninggal dunia pada usia muda), maka perilaku seksual mereka haruslah senantiasa ’aman’ dan ’sehat’, dengan melakukan ABCD. Dengan demikian remaja dikatakan sudah memiliki perilaku seksual yang bertanggung jawab.
Apakah kampanye ABCD itu? A adalah Abstinensia, artinya bahwa mereka tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ini adalah sebuah informasi yang benar, yang harus kita dukung kampanye dan implementasinya. Kita harus membuat remaja melihat (dengan proses edukasi dan sosialisasi) bahwa inilah satu-satunya pilihan bagi mereka, kalau mereka belum menikah. Dan bahwa melakukan seks sebelum menikah adalah kesalahan, keharaman, yang membawa kerugian tidak hanya sekarang di dunia, namun juga kelak di akhirat. Sembari kita ciptakan lingkungan yang kondusif di sekitar remaja kita agar mereka mudah untuk mencegah diri dari melakukannya, baik karena faham atau karena terpaksa (’takut’ terhadap ancaman sanksinya).
Sayangnya, pada pendidikan KRR ini, Abstinensia (A) hanyalah salah satu opsi yang bisa diambil oleh remaja kita, dan bukannya satu-satunya opsi. Terlebih ketika dikaitkan dengan informasi awal yang mengatakan bahwa melakukan eksplorasi seksual pada masa pubertas ini adalah sesuatu yang wajar. Sehingga kalaupun ternyata mereka tidak bisa bertahan untuk memilih opsi Abstinensia (A) adalah suatu hal yang wajar juga. Karena itulah ada pilihan lain yang bisa diambil, yakni B (Be faithful) atau setialah. Pada siapa? Tentu saja kalau pertanyaan ini ditanyakan, secara teori akan kita dapatkan jawaban: setia pada suami dan istri masing-masing tentunya. Tapi, pada konteks KRR ini, benarkah yang dimaksud setia di sini adalah agar para remaja kita setia pada suami atau istri mereka? Apakah benar siswa-siswi setingkat SMP-SMA yang menjadi sasaran pendidikan KRR ini memiliki suami/istri? Tentu saja tidak!. Lalu apa maksud dari mereka harus setia di sini? Mereka harus setia pada siapa? Di titik inilah celah liberalisasi seksual di kalangan remaja kita justru dibuka oleh ’pendidikan’ ini. Karena yang dimaksudkan di sini adalah agar remaja kita setia pada pacar atau pasangan mereka. Lalu apa makna tersirat yang bisa dipahami oleh remaja kita dengan adanya pilihan ’setialah pada pasanganmu’ kalau kamu tidak bisa ’abstinensia/puasa seks’ sebelum menikah? Bukankah itu artinya adalah bahwa mereka boleh ngeseks, asalkan dengan pacarnya, dan mereka melakukannya hanya dengan pacarnya (setia) saja. Apakah ini yang disebut ’pendidikan’?Ataukah ini adalah ’penyesatan’ yang dibungkus label ’pendidikan’?!
Aroma penyesatan (liberalisasi) pada pendidikan KRR ini pun lebih jelas lagi, ketika diberikan opsi berikutnya yakni use Condom (C) seandainya remaja kita (dalam melakukan eksplorasi seksualnya tadi) tidak bisa setia (baca: hanya melakukannya) dengan pacarnya. Bukankah implisitnya itu berarti kita membolehkan mereka bergonta-ganti pasangan, asalkan mereka memakai kondom. Dikatakan, kondom memiliki dual protection. Dengan kondom mereka bisa terproteksi dari kemungkinan terjadinya kehamilan tidak diinginkan, dan juga dari tertularnya penyakit menular seksual. Singkatnya, remaja kita bisa tetap memiliki perilaku seksual yang aman dan sehat (meski bergonta-ganti pasangan) dengan kondom. Jargon yang digembar-gemborkan: ‘safe sex use condom’. Pertanyaannya sekarang: Apakah ini adalah informasi yang benar?
Secara factual, kondom terbukti tidak mampu mencegah penularan HIV. Hal ini karena kondom terbuat dari bahan dasar latex (karet), yakni senyawa hidrokarbon dengan polimerisasi yang berarti mempunyai serat dan berpori-pori. Dengan menggunakan mikroskop elektron, terlihat tiap pori berukuran 70 mikron, yaitu 700 kali lebih besar dari ukuran HIV-1, yang hanya berdiameter 0,1 mikron. Selain itu para pemakai kondom semakin mudah terinfeksi atau menularkan karena selama proses pembuatan kondom terbentuk lubang-lubang. Terlebih lagi kondom sensitif terhadap suhu panas dan dingin, sehingga 36-38% kondom sebenarnya tidak dapat digunakan. Ini terbukti adanya peningkatan laju infeksi sehubungan dengan kampanye kondom 13-27% lebih.
Secara rasional, di saat budaya kebebasan seks tumbuh subur, ketaqwaan yang kian tipis (bahkan mungkin tidak ada), kultur yang kian individualistis, kontrol masyarakat semakin lemah, kemiskinan yang kian menghimpit masyarakat, maraknya industri prostitusi, dan ketika seseorang tidak lagi takut dengan ancaman ’azab’ Tuhan, melainkan lebih takut kepada ancaman penyakit mematikan ataupun rasa malu karena hamil di luar nikah, maka kondomisasi dengan propaganda dual proteksinya jelas akan membuat remaja semakin berani, ’nyaman dan aman’ melakukan perzinahan. Sekalipun sebenarnya kondisi ’nyaman dan aman’ tersebut adalah semu. Mengapa semu? Karena seks bebas akan tetap dimurkai Allah SWT meskipun menggunakan kondom.
Sementara opsi D (no Drug) disampaikan karena saat ini mulai ada trend peningkatan penularan HIV-AIDS melalui penyalahgunaan narkoba (terutama suntik). Opsi no Drug yang berarti ‘jangan pernah menggunakan narkoba’ adalah sebuah content kampanye yang benar, sebagaimana content kampanye Abstinensia (tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah). Sayangnya, lagi-lagi, kampanye ini tidak pernah berani dengan tegas mengatakan bahwa itulah satu-satunya opsi yang boleh diambil oleh remaja kita sembari kita ciptakan lingkungan kondusif agar remaja kita tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Justru sebaliknya, belum all out mengupayakan hal tersebut, kampanye ini justru memperkenalkan ‘strategi’ baru untuk tetap bisa menggunakan narkoba namun dengan resiko yang lebih rendah ketimbang menjadi pengguna narkoba suntik (penasun). Strategi itu kita kenal dengan istilah ‘harm reduction, yakni tindakan memberikan jarum suntik steril dan subsitusi metadon bagi penyalahguna NARKOBA suntik. Benarkah upaya ini akan mengurangi risiko penularan HIV/AIDS? Jawabannya jelas tidak. Mengapa?
Subsitusi adalah mengganti opiat (heroin) dengan zat yang masih merupakan sintesis dan turunan opiat itu sendiri, misalnya metadon, buphrenorphine HCL, tramadol, codein dan zat lain sejenis. Subsitusi pada hakekatnya tetap membahayakan, karena semua subsitusi tersebut tetap akan menimbulkan gangguan mental, termasuk metadon. (Hawari, D. , 2004) Selain itu metadon tetap memiliki efek adiktif. (Bagian Farmakologi. FK. UI. Jakarta.2003) Sementara itu mereka yang terjerumus pada penyalahgunaan NARKOBA termasuk para IDU pada hakikatnya sedang mengalami gangguan mental organik dan perilaku, dimana terjadi kehilangan kontrol diri yang berikutnya menjerumuskan para pengguna NARKOBA dan turunannya tersebut pada perilaku seks bebas.
Adapun pemberian jarum suntik steril kepada penasun agar terhindar dari penularan HIV/AIDS, jelas merupakan strategi yang sangat absurd. Ketika seorang pemakai sedang ’on’ atau ’fly’ karena efek narkoba suntik tersebut, mungkinkah masih memiliki kesadaran untuk tidak mau berbagi jarum dengan teman ’senasib sepenanggungannya’?! Di saat seperti itu, masihkah mereka memiliki kesadaran yang bagus tentang bahaya berbagi jarum suntik bersama, padahal pada saat yang sama mereka sudah lupa (baca: tidak sadar lagi) bahwa memakai narkoba suntik sebagaimana yang mereka lakukan sekarang -dengan atau tanpa berbagi jarum suntik- adalah hal yang membahayakan kesehatannya?! Lagi pula, sudah menjadi hal yang dipahami bahwa mereka-mereka yang sudah terlanjur ’terperangkap’ dalam jerat gaya hidup yang rusak ini biasanya memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang sangat tinggi dengan teman-temannya sesama pemakai. Dari temanlah mereka pertama kali mengenal narkoba, dan bersama teman jugalah mereka kemudian bersama-sama berpesta narkoba. Hal ini dibuktikan oleh tingginya angka kekambuhan akibat bujukan teman-teman. Dan biasanya setiap pemakai memiliki peer group dengan anggota 9-10 orang.
Simpulan dan Penutup
Sebenarnya aroma liberalisasi ini kalau kita mau jernih dan jujur bisa kita lihat sejak dari tujuan apa yang ingin diraih dengan dilakukannya pendidikan KRR ini: ’sekedar’ mewujudkan perilaku seksual remaja yang sehat dan aman, bukan mewujudkan perilaku seksual remaja yang ’benar’. Maka standard yang dipakai bukanlah halal-haram atau benar-salah. Masalah perilaku seksual remaja ini hanya dipandang sebagai masalah medis saja. Yakni bahwa banyak remaja kita yang menjadi korban di tempat-tempat aborsi dan menjadi pengidap penyakit mematikan, meregang nyawa hingga kehilangan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya menjadi generasi masa depan, karena itu harus diselamatkan. Caranya dengan mencegah mereka dari mengalami kehamilan tidak diinginkan (mewujudkan seks aman), dan mencegah mereka dari tertular penyakit menular seksual (mewujudkan seks sehat), tanpa melihat lebih ke akar masalah mengapa hal tersebut terjadi. Alhasil, pendidikan KRR yang diharapkan bisa merubah perilaku seksual remaja yang saat ini sudah begitu liberal tidak hanya mengalami kegagalan, namun malah menimbulkan masalah baru yakni semakin liberalnya perilaku seksual remaja kita saat ini.
Bila dicermati secara seksama, muatan liberalisasi seks yang kental dalam kampanye ABCD ini memang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang mendasari gagasan kampanye ABCD itu sendiri. Yaitu gagasan pemenuhan hak-hak reproduksi yang tidak harus dalam bingkai pernikahan. Pandangan ini disampaikan pada Konferensi Wanita di Bejing, tahun 1975 dan dikuatkan pada Konfrensi Kependudukan Dunia Tahun 1994 di Kairo (ICPD, 1994). Dari konferensi inilah bertolak strategi-strategi penanganan masalah reproduksi yang saat ini diterapkan di dunia, termasuk Indonesia.
Sejatinya strategi-strategi tersebut, termasuk diantaranya konsep pendidikan KRR ini adalah sebuah konsep yang lahir dari paradigma berfikir yang sekuleristik, liberalistik, materialistik dan individualistik. Dikatakan liberalistik karena menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan, termasuk pengaturan dalam memenuhi naluri seksual ini. Liberalistik karena menjadikan kebebasan individu termasuk kebebasan bertingkah laku/kebebasan mengatur kehidupan reproduksi sebagai hal yang diagung-agungkan bahkan diatas pengaturan Tuhan/agama. Materialistik karena menjadikan nilai-nilai materi dan kenikmatan fisik sebagai ukuran kebahagiaan yang harus dikejar. Individualistik karena menjadikan problematika perilaku seksual remaja ini menjadi permasalahan individu remaja itu sendiri, yang akan dianggap selesai begitu sang remaja tersebut mau menanggung akibat/resiko dari perilaku seks bebasnya.
Dari sini, bisa kita lihat banyaknya kalangan yang menolak Konsep KRR ala ICPD ini bukanlah sebuah penolakan yang membabi-buta terhadap semua hal yang berbau ’Barat’ ataupun penolakan tanpa alasan. Akan tetapi lebih karena kesadaran akan bahaya ’penyesatan’ dan ’liberalisasi’ terhadap generasi yang ada di dalam konsep pendidikan KRR ini. Sebuah ‘penyesatan’ dan upaya ‘liberalisasi’ remaja kita yang dibungkus rapi atas nama Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja. Akankah kita menerima dan ikut-ikutan mengkampanyekannya hanya karena itulah strategi yang ditawarkan oleh UNAIDS dan WHO? Sudah saatnya negeri yang dikenal relijius ini merumuskan sendiri strategi penanganan masalah reproduksi remaja yang berparadigma Ilahiyah. Wallahu A’lam.