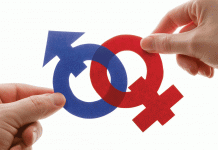Oleh: dr. Aulia Rahman (Anggota HELPS)
Seorang dokter yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita bahwa ada yang berubah saat dia iseng bertanya pada seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan tentang berapa jumlah anak yang diinginkan. Jika dulu mayoritas hanya akan tersenyum dan tersipu sambil menjawab ‘terserah suami’ atau jawaban-jawaban senada, maka jawaban yang belakangan kerap dia dapatkan — meski tetap sambil tersipu, adalah ‘dua anak saja’. Sebagai seorang dokter, hal ini ‘menggembirakan’ karena bisa jadi program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan sejak akhir tahun 70-an oleh Pemerintah, mulai menampakkan hasil.
Benarkah demikian? Ternyata tidak juga. Jawaban tersebut ternyata tidak sejalan dengan data terakhir total fertility rate (TFR) di Indonesia. Di negeri ini, TFR berkisar antara 4.1 dan 5.0, masih cukup tinggi jika dibandingkan Jepang dengan TFR 1.4, lalu China 1.4, bahkan Korea Selatan lebih rendah yakni 1.2. Rerata negara di Eropa berkisar 1.5. Meski memang negara-negara Afrika masih lebih tinggi dengan kisaran di atas 5 atau 6.
Begitu juga dengan data dari Badan Pusat Statistik tentang persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB, angka totalnya hanya 59.98% pada 2015, bahkan turun dari dua tahun sebelumnya yakni 61.98% dan 61.75% pada tahun 2013 dan 2014. Dari angka total tersebut sendiri, sebarannya pun tidak merata, tercatat propinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah pemakai KB tertinggi yakni 70.13% dan Papua terendah dengan tak sampai sepertiga yakni 23.37%. Estimasi jumlah penduduk juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2035, diperkirakan negara ini akan dihuni oleh ±305.652.400 dari jumlah tahun 2015 yakni ±255.461.700.
Jumlah tersebut tentu sebenarnya merupakan sumber daya manusia yang luar biasa jika diberdayakan dengan baik dan benar oleh Pemerintah. Namun berkaca dari pengalaman sebelumnya, peningkatan jumlah penduduk ini kerap justru dianggap sebagai masalah karena tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sehingga alih-alih berdaya guna, generasi tersebut malah jadi beban. Tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 10.86% pada Maret 2016 yang lalu, dan tak sampai setengah dari jumlah penduduk negeri ini yang punya jaminan kesehatan, yakni sekitar 172.620.269 jiwa saja. Padahal jika ditinjau dari kurva demografis sebaran usia, Indonesia sebenarnya punya potensi besar dengan lebih dari setengah jumlah penduduknya masih berusia di bawah 30 tahun, dan hanya sekitar 6-7% berusia di atas 65 tahun ke atas.
Namun sumber daya ini tak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan kesadaran akan ancaman krisis populasi yang telah melanda beberapa negara maju dengan TFR rendah. Kebijakan pengendalian kelahiran hendaknya tidak sekedar bertujuan untuk menekan lonjakan angka penduduk namun lebih kepada penekanan lahirnya generasi-generasi bangsa yang ‘sakit’. Karena jika tidak, kita akan ikut terjebak dalam krisis kehilangan generasi akibat tak adanya lagi keinginan untuk memiliki banyak keturunan. Didukung dengan angka harapan hidup yang makin tinggi, bukan tidak mungkin, masalah yang negara-negara luar tersebut hadapi, akan terjadi di negeri ini, jika kita tak bijak dalam mengambil langkah pemecahan masalah lonjakan jumlah penduduk.
Kembali pada pertanyaan semula, dengan derasnya aliran arus liberalisme, hedonisme, dan sekularisme yang melanda negeri ini, pernikahan memang tak lagi dipandang sebagai sarana yang sejati untuk meneruskan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT, melainkan hanya sebagai alternatif tujuan hidup atau sekedar check point dari berbagai tujuan hidup yang sebagian besar berkisar pada kenikmatan duniawi. Terlebih saat kini pergaulan semakin bebas, generasi muda sudah tak lagi menginginkan pernikahan karena mereka telah bisa mendapatkan pemuasan nafsu seksualnya tanpa harus menikah secara sah.
Selain masalah tersebut, tingginya angka remaja yang melakukan hubungan seksual dini, kehamilan di luar nikah, aborsi, dan penggunaan obat-obatan terlarang tentu jadi tanda tanya tentang sejauh mana sebenarnya keberhasilan kita dalam menghasilkan generasi sehat penerus bangsa.
Di dalam Islam, terdapat banyak ajaran tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, misalnya ajaran pemisahan kehidupan antara laki-laki dan perempuan di luar wilayah umum, maupun aturan tentang menutup aurat, ini semua telah dilakukan sejak dini di bingkai pendidikan dalam keluarga. Jika langkah-langkah seperti ini telah dilaksanakan dengan luas, seharusnya tidak perlu lagi ada kebingungan tentang kapan pendidikan seks diajarkan, atau tentang pakaian yang layak digunakan di ruang publik. Begitu pula tentang kesehatan reproduksi, bukankah Nabi SAW sendiri telah mengajarkan dalam haditsnya bahwa wanita itu biasa dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kemuliaan keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka, pilihlah yang beragama, karena kalau tidak niscaya engkau akan merugi” (HR. Bukhari No. 5090, Muslim No. 1466).
Namun lebih dari itu, kita tahu masalah yang dihadapi bangsa ini lebih dari ‘sekadar’ jumlah populasi yang melonjak, atau angka kemiskinan yang naik, atau capaian kesehatan yang masih rendah, namun keterkaitan poin-poin tersebut yang hanya bisa diselesaikan dengan suatu solusi yang bersifat sistemik pula. Selain pendidikan dan sistem kesehatan yang benar, diperlukan upaya pencegahan yang tegas dari Pemerintah dalam membendung arus liberalisasi dan sekularisasi di negeri ini.
Tidak bisa tidak, perlu aturan-aturan yang lebih tepat dalam menyasar akar permasalahan lonjakan jumlah penduduk di negara ini, bukan sekedar mengurangi angka kelahiran tentunya. Hingga kelak, seorang dokter tak lagi merasa sungkan untuk ‘menasihati’ kala pasiennya merasa ‘takut’ untuk punya anak lebih dari dua. Hingga nanti, kita semua tidak akan perlu ragu dan bimbang lagi, untuk sama-sama menua di Indonesia, Bumi Allah SWT. (AR)